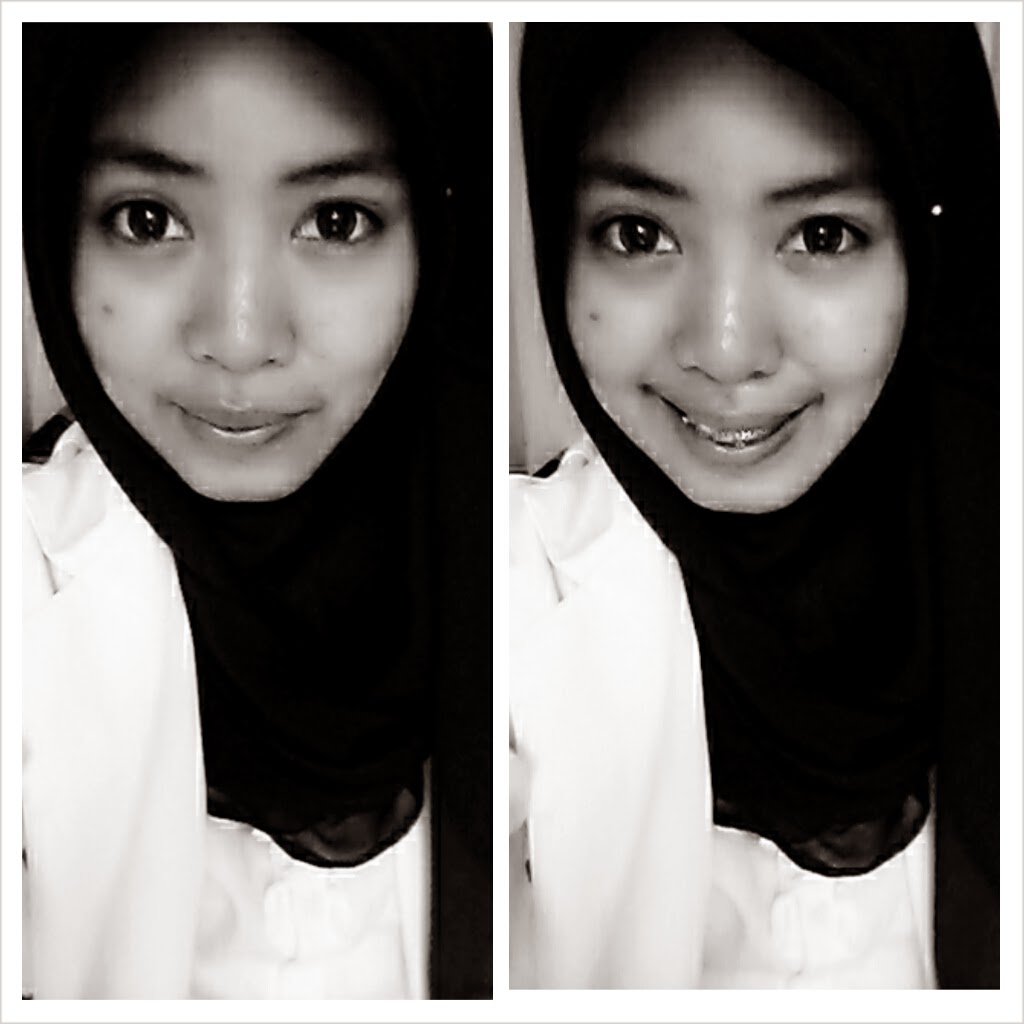Gue dany, dan hampir aja gue lupa gue punya blog.
Well then, kemarin waktu gue nungguin kuliah jam 2 di nangor karena kuliah pertama kosong *dan gue dr bandung jam 6 pagi buat kuliah pertama*, gue dikasih buku bagus sama temen gue.
Judulnya taste buds. Taste buds ini kayak kumpulan cerpen2 gitu. I have no choice but read it in case I'm deadly so bored there.
Gue bener-bener baca tanpa prasangka kalo buku ini bakal bikin perasaan gue campur aduk.
Bahkan ada salah satu cerpen yang gue sukaaaaa banget, dan bodohnya gue baca pas kuliah forensik, yang bikin gue mewek di tengah expresi muka-muka orang tegang ngeliatin gambar mayat di slideshow.
Oke, cerpen yang gue baca itu judulnya "Bangga", which reminds me about my lovely father.
Dan saking sukanya gue, gue bakal ketik semua di sini biar, well, *mungkin* merasakan apa yang gue rasakan.
Don't grab your cookies, or anything, just read, and let your feeling flows.
BANGGA
Ayah tak pernah melarang, dibiarkannya aku besar dengan luka-luka, sekali patah tangan, sekali terinjak kaca, dan baret di pipi kanan. Waktu itu, pipiku disambar ujung sepatu pak lurah karena nekat mencuri mangga di halamannya siang-siang bolong.
Ayah tak banyak bicara, raut wajahnya tenang, menghadapi kepala sekolah yang sudah hampir meledak. Aku lupa apa masalahnya. Klise, kemungkinan besar karena bolos, ketahuan mencoba merokok atau mencontek. Pulang dari situ, dalam perjalanan menuju ke rumah, ayah menghentikan mobil dan menatapku dalam-dalam.
"Ayah malu", ujar beliau singkat.
Sejak kejadian itu, aku bersumpah tidak akan membiarkan ayah mengulang dua patah kata itu lagi selama-lamanya.
Ayah rajin menabung. Rumah kami tidak diisi perabot mahal. Televisi hanya satu, diletakkan di ruang tamu, untuk menghibur keponakan atau saudara-saudara jauh kalau mereka menginap atau berkunjung. Pajangan hanya dua pasang, keramik gajah dari Thailand, itu pun hadiah dari kawan dekat ayah.
Tapi bagaimanapun kami jarang meminjam uang. Uang sekolahku cukup mahal, pendaftarannya ayah bayar lunas. Kakak pertamaku kuliah di Australia, kirimannya tidak terpurtus sampai dia lulus. Pernikahan mas Deden di gedung besar yang sewanya ratusan juta, ditanggung sendiri oleh ayah karena pihak perempuan tinggal di luar daerah.
Ayah itu agamis, beliau puasa senin kamis, shalat berjamaah di masjid depan rumah, ikut menyembelih dan membagi-bagikan hewan kurban untuk warga sekitar.Rotan adalah kata pengganti untuk melecuti kami bila malas sholat. Walau begitu, rotan ayah jarang digunakan. Beliau mendidik kami untuk mencintai agama, bukan takut rotan.
Ayah itu penyayang. Ketika kami kecil, beliau mengantar dan menjemput kami dari sekolah satu per satu. Dulu belum ada mobil, dan sepeda motor hanya muat untuk dua orang dewasa. jadi aku dan kakak dijemput dulu, diturunkan di rumah. Lalu ayah pergi lagi mengambil mas Deden di sekolahnya.
Beliau memanjakan kami dengan makanan. Beliau juga pandai membuat mainan tradisional. Aku ingat betapa bangganya aku dengan layangan yang dibuat dan diraut oleh ayah. Dua puluh kali diadu tidak pernah kalah.
Malang, pada aduan ke duapuluh satu, benangnya putus. Aku mengejarnya mati-matian sampai melompati pagar segala. Itulah sejarahnya aku menginjak kaca. Layang-layang itu akhirnya kusimpan di gudang dan ketemu kembali menjelang aku mahasiswa.
Ayah juga tak luput dari kelemahan dan kekurangan. Ayah tidak bisa berbahasa Inggris. Beliau takut sekali kami mewarisi kelemahan tersebut hingga ketiga anaknya disekolahkan jauh-jauh.
Ayah seumur hidupnya paling susah diajari teknologi baru. Mengetik sms, pelaaaaan sekali. Memakai komputer takut-takut. "Takut meledak tiba-tiba", katanya.
Di kantornya, ayah juga terlambat naik pangkat. Aku ingat teman seruangannya sudah jadi kepala cabang, ayah masih juga di ruangan itu. Paling tinggi jadi kepala bagian. Kurasa karena ayah banyak diam. Orang-orang berpikir beliau tidak bisa bekerja. Zaman sekarang yang dilirik kan, yang paling berkoar-koar.
Dan dari semuanya itu yang paling kukagumi adalah perlakuan ayah terhadap ibu. Ayah memegang kendali keluarga, namun menyerahkan dan memercayakan hal-hal rumah tangga pada ibu.
Ayah pernah memasakkan ibu sepiring nasi goreng. Pernah mencucikan ikan bawal. Pernah ikut ibu ke pasar, walaupun beliau jalan di belakang, sibuk toleh kanan-kiri terpesona dengan suasana yang begitu hiruk pikuk, bau bercampur baur, dan cara-cara kreatif pedagang agar jualannya dilirik orang.
Ayah membersihkan langit-langit dan bagian atas lemari yang susah ibu jangkau. Lalu setelahnya, tidak mengeluh, hanya minta dibuatkan teh dan pisang goreng. Ayah memang terlalu kaku untuk memuji kecantikan ibu. Tapi beliau membuktikannya dengan menjaga pandangannya terhadap wanita lain.
**********
Sekarang aku dan ayah berhadap-hadapan. Aku fokus pada ikrar yang akan kuucapkan, pada tanggung jawab yang akan kupikul, dan pada kepercayaan keluarga di sebelah sana, untukku agar menjaga anak gadis mereka sebaik mungkin. Setelah nanti gelarnya akan berubah, nama belakangnya akan berganti, dan temoat tinggalnya akan berpindah.
Ayah menatapku, "Kamu siap?"
Aku membalas tatapan teduh beliau, "InsyaAllah, Fadllan siap, Yah."
Ayah tiba-tiba memelukku erat. Dapat kurasakan tangannya bergetar dan beliau bersusah payah menahan tangis agar tidak pecah. Aku terkejut bukan main. Pelukan ayah-anak seperti itu tidak lagi kualami sejak umurku delapan tahun. Aku dan ayah tidak selamanya harmonis. Kami pernah berperang dingin seminggu lebih setelah ayah mengucapkan "Ayah malu," mengingat waktu itu aku adalah anak SMA yang egonya lebih tinggi dari akal sehat.
Aku pernah menyayangkan kenapa ayah bukan konglomerat yang bisa menghadiahiku mobil sport untuk upah lulus cum laude. Aku adalah bungsu yang paling merepotkan, paling menyita waktu dan tenaganya, dan entah kapan membanggakannya.
Ketika ayah melepaskan pelukannya, aku menyadari mata beliau sudah basah.
"Ayah bangga," ujarnya parau.
Aku tercekat. Tanpa pikir panjang, akulah yang ganti merangkul beliau erat-erat, manangis meraung seperti bocah delapan tahun. Hari ini untuk pertama kalinya dalam dua puluh lima tahun hidupku, aku merasa begitu bersyukur karena ayah, adalah ayah.
*******fin******
I dont know, dari sekian banyak cerita tentang ayah, this is the most favorite. Mungkin karena deskripsi ayah di sini 99% sama kayak bapak. Sifatnya, cara berpikirnya, dan hampir semua yang di lakuin ayah di cerpen itu pernah dilakuin bapak.
Bapak yang rajin nabung (terutama buat kuliahku yang, yah, begitulah) jadi hidup kami terbiasa untuk ‘biasa-biasa’ saja, bapak yang rajin sholat jamaah di masjid, bapak yang nggak pernah marah, bapak yang nggak bisa bahasa inggris, bapak yang nggak update teknologi, bapak yang bantuin ibu pekerjaan rumah (bahkan pagi bapak yang masak nasi), bapak yang selalu mentingin kepentingan anak-anaknya dari pada dia sendiri, bapak yang selalu antar-jemput anaknya waktu sekolah (bahkan danang, adik-gue-yang-udah-SMA-dan-tingginya-se-pohon-pinang yang ke sekolah bawa motor dan belum balik pas maghrib, dijemput bapak ke sekolahnya jalan kaki), bapak yang sayangnya sama ibu level over 9000. Sama banget, samaaa banget.
Jadi gue baca novel ini, kayak gue baca biografi bapak. Hehehe.
Di keluarga gue mungkin nggak terbiasa dengan pengungkapan kata-kata sayang, gue ga biasa bilang “Aku sayang bapak” or “Aku sayang ibu”, tapi semoga mereka bisa ngerti bentuk lain dari sayang gue ke mereka. Setiap detik gue berdoa biar mereka selalu sehat, baik-baik saja, dan dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan. Gue nggak pernah ngeluh ke mereka, about things that maybe go not well enough here. And I swear that I’ll do anything for make them happy, make them proud of me, whatever it takes :)